Judul : Fifty Years of Silence
Penulis : Jan Ruff O'Herne | Terbit : 2011
Jumlah Halaman : 200 | Harga : Rp. 15.000 (dengan diskon)
paperback
Sinopsis :
Jan Ruff-O’Herne berasal dari sebuah keluarga kolonial yang lahir di
Jawa pada tahun 1923. Masa kecilnya penuh keceriaan dan kebahagiaan di
daerah perkebunan pabrik gula Tjepiring, dekat Semarang, Jawa Tengah.
Kebahagiaan ini harus berakhir seiring berakhirnya masa penjajahan
kolonial Belanda di Indonesia ketika Jepang berhasil menyerbu Pulau Jawa
tahun 1942. Bersama ibu dan kedua adiknya, Jan Ruff-O’Herne diasingkan
di kamp penjara Ambarawa.
Masa-masa sulit untuk bertahan hidup
dengan segala keterbatasan di kamp penjara Ambarawa dijalani Jan bersama
ribuan perempuan dan anak-anak Belanda. Ketika usia Jan menginjak 21
tahun, Jan bersama tujuh orang gadis Belanda dipindahkan ke sebuah rumah
bordil di Semarang untuk dijadikan budak seks para tentara Jepang
selama tiga bulan. Setelah itu, mereka dipindahkan ke sebuah kamp
penjara di Bogor untuk kemudian dipindahkan kembali ke kamp Kramat,
Batavia. Disinilah Jan bertemu dengan Tom Ruff yang akan menjadi
suaminya kelak.
Selama lima puluh tahun, Jan tidak pernah
memberi tahu siapa pun tentang peristiwa yang dialaminya semasa perang
tersebut. Pada tahun 1992, Jan memutuskan angkat bicara dan mendukung
para korban pemerkosaan Perang Korea memohon keadilan. Jan berjuang
sekuat tenaga untuk membela hak-hak kaum wanita dalam perang dan konflik
bersenjata.
Jan dan teman-temannya saat berkampanye memeperjuangkan hak keperempuanannya
Resensi :
Menurutku buku ini bagus untuk memperluas wawasan kita mengenai bagaimana keadaan Indonesia --dan sebagian warga Belanda-- saat Jepang menyerang negara Indonesia. Buku yang ditulis sendiri oleh Jan tidak hanya mengulas dari sisi kemiliteran tentara Jepang saja, tetapi juga mengulas sisi psikologis maupun ekonomi penduduk Indonesia --dan Belanda ex penjajah Indonesia. Gambaran mengenai bagiamana orang-orang Belanda yang masih "berdomisili" di Indonesia diperlakukan sangat miris oleh pasukan Jepang, juga gambaran mengenai keakraban yang terjalin antara keluarga Belanda dengan keluarga pribumi saat Jepang belum memasuki Indonesia, berhasil disampaikan dengan gaya bahasa yang meyakinkan. Tidak heran jika berkat kepandaiannya mengolah kata-kata inilah, teman-teman senasib Jan yang 'dijajah' hak perempuannya diberbagai belahan negara lainnya berani menyuarakan dan menuntut haknya kembali setelah 50 tahun terpenjara dalam diamnya sendiri.
Setelah berdiskusi dengan teman yang juga pernah membaca buku ini, aku berpikir bahwa buku 50 Years of Silence ini bisa saja menuai berbagai kritik dan kontroversi. Karena apa? Jan menggambarkan seakan-akan masyarakat Indonesia ikut serta dalam gerakan-gerakan penindasan terhadap warga Belanda yang saat itu masih tinggal di Indonesia, Jan beranggapan bahwa masyarakat Indonesia mau "ikut" dengan kebijakan-kebijakan yang pernah ditetapkan Belanda pada masa itu. Aku sebagai masyarakat Indonesia yang membaca buku ini, tentu menolak dengan anggapan-anggapan Jan itu. Baik Belanda maupun Jepang sama-sama tidak memiliki hak untuk menjadikan masyrakat Indonesia sebagai pesuruh/budaknya. Di buku ini dijelaskan pula bahwa lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia pada masa itu
sangat tergantung pada keluarga Belanda. Sebagaian besar masyarakat
Indonesia yang perempuan bekerja menjadi pembantu rumah tangga di rumah keluarga Belanda, sedangkan saat Jepang mulai menjajah Indonesia, Jan menggap bahwa orang-orang Jepang merampas pekerjaan orang indonesia, orang jepang (menjajah dan) menelantarkan masyarakat pribumi dan masyarakat Belanda yang tinggal di Indonesia.
Saya khawatir terhadap pembaca buku yang sudah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa ini nantinya akan menganggap bahwa Indonesia juga terlibat dalam aksi ke-tidak berperikemanusiaan-an terhadap warga Belanda --yang dibuku ini digambarkan bahwa Belanda tidak seburuk penjajah-penjajah lainnya.
rating : 4/5
rating : 4/5








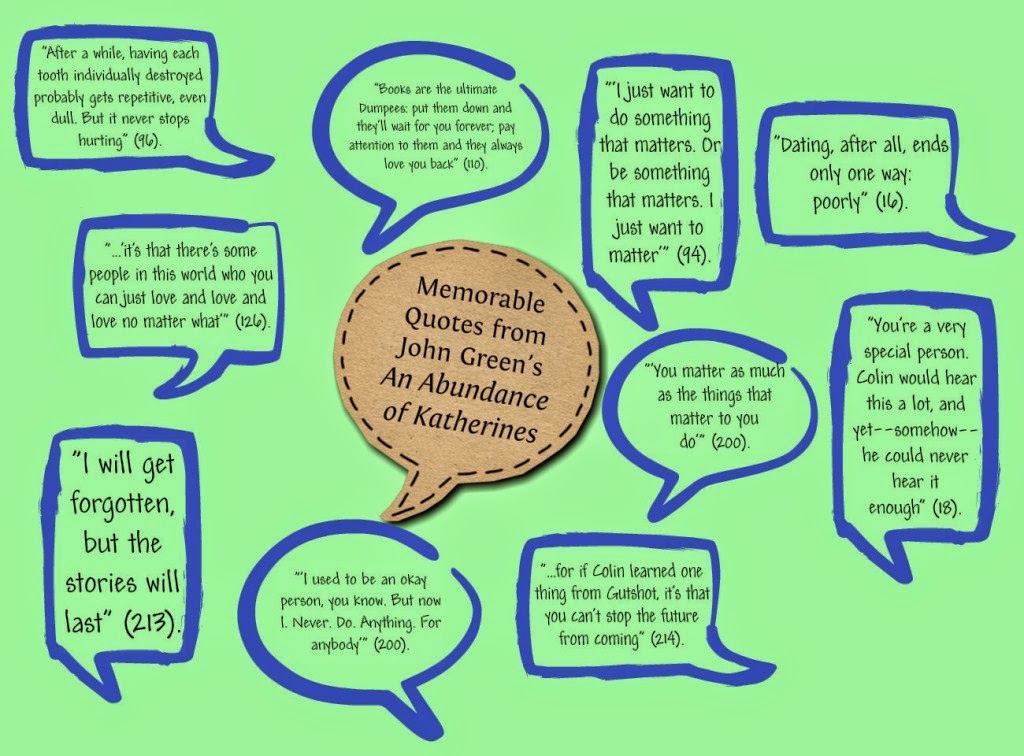





+image.jpg)
+image1.jpg)
+image2.jpg)